Cerpen ini dimuat di buku antologi The Secret Admirer. Masih karya Syarifah Lestari. Dibukukan bersama cerpen karya Via Rinzeani, Oqiesy, dan Sugih. Kalau ada yang mau baca cerpen lainnya, silakan mampir ke Rumah Belajar Pertamina, Kota Jambi.
Kalau gak mau ya sudah! Nonton trending Youtube aja biar hedon. Isy apaan sih!
Mata Ayah
Tempat ini mungkin tak nampak seperti pelabuhan, tak layak disebut pelabuhan, atau memang ia bukan pelabuhan. Hanya sepotong ruangan menyerupai pos ronda, satu sisi menghadap pasar, tiga lainnya melulu air.
Aku
duduk menampung angin, tak menunggu siapa pun layaknya orang-orang yang berada
di sebuah tempat berlabuh. Kata pelabuhan sudah total tak bisa disandingkan
pada pos ini sekarang. Pasar sudah mati, lebih dari separuh penduduk dusun
pergi meninggalkan tanah tak berpenghasilan ini. Pos yang semula kuanggap
pelabuhan, kini pantas disangka jamban.
Sejak
krisis tahun 1998, pabrik kayu yang semula menjadi sandaran hidup masyarakat,
bangkrut. Semua karyawan di-PHK. Semua, tanpa sisa. Akibatnya, tanah dusun kini
mengambang karena lebih dari separuh manusia yang semula memberatinya, pergi
jauh ke kota, bahkan menyeberangi pulau untuk penghidupan yang lebih
memungkinkan. Tanjung Jabung hanya berisi tanah gambut. Di mana-mana rawa, tak bisa ditanam apa pun,
bahkan jenazah sekalipun harus dipeti dan diberi pemberat. Tanah tak bisa
diandalkan, di sini air menjadi raja.
Di
muka pos, kulihat Ayah melambai. Perahu yang membawanya menjauh, tapi gambar
matanya yang memerah, masih tinggal di hatiku. Ayah pergi menyelamatkan
kelakiannya, meninggalkan hukuman pada perempuan yang dulu ia kasihi.
Kelak
jika kau sudah mengerti, susul Ayah. Atau Ayah akan menjemputmu, pesannya sepuluh tahun lalu.
Ayah
tak pergi tersebab ambruknya pabrik sawmil. Ia memang karyawan pabrik, tapi ia punya
keahlian lain yang tanpa pabrik itu, ia masih mampu menghidupi kami seperti
sebelumnya. Maka Ibu adalah manusia paling terkutuk atas ketidaksyukurannya
pada nasib.
Angin
laut membelai permukaan sungai, menyapaku sembari menerjang debu-debu halus di Pos
Labuh. Lalu keluar membawa pandanganku pada sisa-sisa pasar yang mati. Kulihat
seorang bujang kecil beradu lari dengan bapaknya, diakhiri lompat indah dari
titian ke muka sungai. Itulah aku dan Ayah lebih dari sepuluh tahun silam.
Kala
itu tidak ada rumah reyot yang tak berpenghuni. Tidak ada tanah lapang dengan
puing-puing sisa bangunan. Semua kediaman berbau khas, aroma cat baru, wangi
deterjen, masakan yang menguar. Layaknya sebuah kampung, ada sekolah, pasar,
tempat bermain.
Jika
mendapat tugas malam, Ayah berangkat ke pabrik segera setelah salat Magrib.
Menjelang subuh, kudengar langkahnya meniti tangga rumah panggung kami. Rumahku
hingga tetangga terjauh semuanya berupa panggung, maka jika seekor kucing saja
berjinjit, penghuni rumah dari ujung ke ujung akan mengetahuinya. Tapi tak ada
yang mampu mengira dengan pasti, di mana tepatnya posisi kucing itu.
Setelah
langkah Ayah menjauh, ada langkah lain yang menggoyang panggung. Besoknya,
sebelum kaki ayah menaiki anak tangga, ada langkah kaki lain menuruni tangga
itu. Semua tahu, tapi tak ada yang tahu pasti, di mana langkah itu, dan siapa
pemiliknya.
Aku
bisa pastikan itu bukan langkah ayahku. Ayah selalu menemuiku setiap kali
hendak keluar atau baru masuk ke rumah. Tapi aku tak tahu siapa. Aku juga tahu
langkah itu berjinjit di rumahku, tapi Ibu melarang aku melihatnya.
Jika
Ayah bertugas siang, langkah misterius itu berganti lompatan. Aku merasakan
hentakan dari kolong bawah rumah. Di kamar Ayah memang terdapat lubang yang
menghubungkannya dengan ruangan di bawah rumah. Ruang itu hanya berisi tumpukan
kayu untuk memasak. Semua sisi berpagar bilah-bilah papan yang dijarangkan. Orang
dewasa berbadan pipih bisa melewati pagar itu, dan selain ayahku sangat berotot,
tak ada alasan baginya menemui ibuku melalui ruang itu.
Kuluruskan
punggung, lalu selonjor di bangku panjang yang renta. Arus sungai menerbitkan
halusinasi, seolah Pos Labuh tengah berlayar melawan alirannya. Kutoleh lagi
pasar untuk mengembalikan kesadaran. Tampak seorang bapak menggendong anaknya
di pundak. Mereka baru saja pulang memancing, memamerkan hasil kesabarannya
pada pedagang ikan di pasar. Itulah aku dan Ayah.
>> Tak kalah seru, cerpen berlatar Jambi pada masa penjajahan Jepang <<
Kemudian
Ibu hamil. Dan akulah yang paling bahagia, sebab sejak lama kupinta adik pada
Ayah. Kuusap perut Ibu, tapi perempuan cantik itu tidak tersenyum. Ayah juga
tak nampak gembira. Orang dewasa punya keanehan yang tak akan kupahami hingga
aku sendiri menginjak usia itu, suatu saat nanti.
“Aku
akan menjagamu!” Janjiku pada adik di perut Ibu. Kata orang, ketika perut Ibu
kian membuncit, saudaraku berjenis kelamin perempuan. Karena Ibu suka
berdandan, agak pemalas, dan gerakan adik lebih banyak di sebelah kiri.
Terserah soal kelogisan, bahkan soal laki-laki atau perempuan. Aku hanya punya
naluri seorang abang yang ingin melindungi.
Suatu
malam, saat hendak ke jamban di belakang rumah, kulihat sesosok bayangan
berkelebat di kamar Ibu. PLN tak sampai ke dusun kami, hanya lampu teplok
setengah menyala menggantung di samping pintu kamar.
“Ayah,”
panggilku, karena kudengar bayangan itu berdehem, suara laki-laki.
Tidak
ada jawaban.
“Ibu,”
kucoba lagi.
“Hmm,
tidurlah! Sudah malam.” Suara Ibu.
“Ada
orang lain di kamar Ibu?”
“Tidak.”
“Boleh
aku tidur di sana?” Tanyaku.
“Tidak.”
Aku
urung ke jamban, ingat janji pada adikku untuk menjaganya. Sebelum Ibu hamil,
aku tak ambil pusing ketika kurasa ada yang keluar-masuk kamarnya, karena aku
yakin Ibu bisa menjaga diri. Kini saudara perempuanku terancam, maka aku
berjaga semalaman itu.
Menjelang
subuh, ada yang melompat turun dari kamar Ibu. Aku rasakan hentakan badannya.
Kuintip dari sela lantai kayu, seorang laki-laki kurus tinggi berjalan pelan
melewati tumpukan kayu bakar, keluar melalui bilah papan, lalu hilang ditelan
gelap.
Tak
lama kemudian, langkah Ayah menghiburku. Ia membuka pintu perlahan, lalu menuju
kamarku.
Ayah
terkejut melihat aku terjaga.
“Ayah
besok tak usah kerja,” kataku padanya.
Ayah
tak terlihat heran dengan permintaanku.
“Ada
orang masuk kamar Ayah, aku khawatir ia mengganggu perut Ibu.” Kutunjukkan
betapa aku sungguh-sungguh meminta.
Ayah
memandangi lantai di sekitar kakinya, matanya mengerjap berulang-ulang seperti
orang salah tingkah.
“Ayah
percaya aku?”
“Sangat.
Ayah tadi bertemu dengan orang itu.”
Sekarang
aku terperangah.
“Tak
apa, ia tidak berbahaya. Kalau kau takut, ikut Ayah saja ke pabrik.”
“Aku
ingin menjaga adik!” Seruku.
“Dia
bukan adikmu.” Ayah berpaling.
“Ayah,”
Ibu memanggil dari kamarnya.
“Ayah
harus bekerja untukmu.” Ayah meninggalkanku. Ia menuju dapur, bukan ke kamar.
Kulirik
jam tangan, pukul 5. Selalu pukul 5 sejak tiga tahun lalu. Jamku rusak. Benda
kanak-kanak di pergelangan tangan kiriku itu adalah benda kesayanganku seumur
hidup. Ayah membelikannya setelah menerima gaji, terlambat 10 hari dari ulang
tahunku yang ketujuh. Benda itu kujaga sebaik-baiknya, tak akan kupakai kecuali
pada hari-hari istimewa. Setiap melihat jam tangan itu, kulihat pula mata Ayah
yang memerah. Begitu dalamnya ingatanku pada matanya, karena Ayahku tak pernah
menangis sebelumnya.
Dan
di Pos Labuh ini, lambaian Ayah melengkapi kerinduanku padanya.
Aku
tertunduk, sekitar mataku kram. Bahuku naik turun. Aku terisak mengenang ayah
yang kupuja. Dan basahlah lantai berdebu di bawahku. “Ayah …,” kupanggil ia.
Hari
ini seharusnya istimewa, karena bertepatan dengan tanggal dan bulan
kelahiranku. Maka aku berada di sini, mengenang berjalannya usiaku. Dan aku
mengenakan jam tangan pemberian Ayah, lalu duduk di Pos Labuh untuk kembali
mengenangnya.
Matahari
turun, kemilaunya melukis bayanganku. Saatnya pulang. Tapi guncangan kecil
menggoyang Pos Labuh, pertanda ada kapal yang datang. Kutoleh hamparan air yang
terbingkai pepohonan tak beraturan, benar saja, sebuah tongkang mendekat.
Aku
tak ambil peduli. Harus segera pulang untuk memenuhi janji.
Sembilan
bulan lebih dua pekan, baru Ibu melahirkan. Ibu dan Ayah sejak lama tak banyak
saling bicara, nyaris tak pernah. Ayah tetap riang jika bersamaku, tapi ia
memang bukan orang yang banyak bicara. Ibu pun demikian.
Ibu
memilih dukun kampung, tapi Ayah berkeras menjemput bidan di dusun sebelah.
Dukun beranak dan bidan saling bantu hari itu, aku melihat kerja sama yang baik
antara manusia medis modern dengan manusia tradisional. Ayah membayar keduanya
sama besar, padahal saat itu krisis tengah memuncak. Aku tak kenal Jakarta,
baru tahu berita reformasi setelah bertahun-tahun kemudian. Tapi imbas
kerusuhan telah sampai di dusun, bahkan masuk ke dalam rumah kami.
Ayah
membersihkan sepetak tanah di belakang rumah. Tanah yang benar-benar tanah,
bukan rawa. Ia tanam bermacam sayuran, lalu memagari tanah kecil itu dengan pohon-pohon
singkong.
Ayah
giat sekali. Setiap hari ia bersepeda entah ke mana, pulang membawa beras,
buah, kopi, gula, … apa saja. Begitu terus selama satu bulan.
Lalu,
di pagi buta. Ayah memasukkan semua pakaiannya ke dalam satu-satunya tas yang
ia punya. Pakaian Ayah memang tak banyak, hingga ransel hitam pudar itu mampu
menampung semuanya.
“Ayah
pergi sepagi ini?” Tanyaku keberatan.
“Ya.
Kau juga,” katanya mengejutkanku.
“Aku
harus menjaga adik.” Aku menolak.
Ayah
menggeleng. “Dia bukan adikmu.”
“Ayah
….” Terdengar suara Ibu, memanggil Ayah dengan sangat lembut. Kupikir Ibu
mendengar percakapan kami.
“Kelak
jika kau sudah mengerti, susul Ayah. Atau Ayah akan menjemputmu,” pesan Ayah
kemudian.
Ia lalu
memunggungiku, lantas berjalan keluar dengan langkah-langkah lebar. Bertahun-tahun
berikutnya baru kusadari, Ayah tak pernah masuk ke kamar Ibu kecuali saat Ibu
melahirkan. Dan ia tidak pernah menggendong adikku, satu kali pun!
Kukejar
Ayah, sambil memanggil-manggilnya. Ayah tetap tak menoleh. Tak ada orang sepagi
itu, apalagi pabrik sawmil telah setahun bangkrut. Hampir semua orang
meninggalkan dusun terpencil ini.
Ayah
melompat ke pelabuhan, sebuah perahu telah menantinya. Tanpa basa-basi, Ayah
menaiki perahu itu dan berdiri di buritan. Matanya bersitatap dengan mataku,
merah dan basah. Seseorang duduk di tengah perahu, mendayung. Langit keunguan
saat perahu itu kian mengecil di pandanganku. Ayah melambaikan tangannya dari
kejauhan.
Ini
ulang tahunku yang kedelapan belas. Aku tak berharap apa-apa, kecuali sedikit
keramaian. Karena ternyata waktu tak mampu menghapus kenangan yang sama sekali
tak ingin kukenang.
“Azhar!”
Seseorang memanggilku. Suaranya membuat darahku berdesir.
Aku
tak hanya menoleh, tapi juga berlari. Ini kado terindah yang pernah kudapat. Ayahku
di tongkang, Ayahku datang! Aku berteriak sekencang-kencangnya dalam hati.
Tongkang
merapat, Ayah meniti pinggiran geladak, lalu dengan sigap melompat ke Pos Labuh.
“Kau
masih mengenal Ayah?” Ia mendekapku.
“Pasti.”
Aku menangis haru.
“Mana
pakaianmu?” Ayah melepaskan pelukannya dan memberiku pertanyaan yang
membingungkan.
“Kau
tak membawa apa-apa?” Tanyanya lagi, membuatku semakin bingung.
“Apa
maksud Ayah?”
“Kau
belum paham, Nak, apa yang terjadi dengan rumah kita sepuluh tahun silam?”
“Sangat
mengerti, Ayah.”
“Dan
pesan Ayah? Kau susul, atau Ayah jemput.”
Aku
mengangguk pelan.
Ayahku
mematung.
“Kupahami
kau tak pulang dengan membawa maaf untuk Ibu. Tapi ampuni aku.” Kucium tangan
Ayah. “Aku akan tetap memegang janji untuk menjaga adikku.”
“Ada
yang lebih pantas bertanggung jawab atas mereka,” balas Ayah.
“Bayangan
yang kulihat semasa kecil itu, tak pernah lagi ke rumah. Adikku panas tinggi
saat belum dua tahun, sekarang ia tak normal.”
“Masih
ada ibunya.”
“Ibunya
terlalu larut dalam penyesalan, entah di mana kesadarannya sekarang.”
Ayah
terdiam.
Pelan,
aku beranjak. Melangkah meninggalkan Pos Labuh, menuju rumah yang kutinggali
sejak belasan tahun lalu. Ayah mengikuti langkahku.
Satu-satunya
rumah panggung yang masih berdiri menanti kami di kejauhan. Beberapa anak
tangga sudah kuperbaiki, bilah-bilah papan yang rusak di bawah kubiarkan saja
demikian. Aku dan Ayah berjalan dalam keheningan. Pasti ribuan kenangan
menghujani memori kepalanya. Dan hatinya berdarah lagi.
Anak
tangga pertama kunaiki, Ayah ragu untuk menyusul. Kubiarkan ia termangu di
bawah. Sampai di atas, kubuka pintu perlahan. Rumah panggung bergoyang saat Ayah
akhirnya menyusulku.
Seorang
perempuan yang tak muda lagi duduk tepat di balik pintu yang terbuka. Rambutnya
kusut, matanya sayu dan selalu bengkak. Ia sudah tak mampu bicara, kecuali
ceracau tak jelas yang intinya adalah kemarahan pada diri sendiri. Tak ada
reaksi berarti saat ia lihat aku datang. Ibuku memang lama tak berdiri, entah
tak mampu atau tak mau. Ia ke sana kemari dengan merangkak serupa bayi,
demikian pula adikku.
Kemudian
Ayah menyusul muncul di muka pintu. Terjadi begitu saja, Ibu meraung-raung
mendekatinya. Ia merangkak cepat meraih kaki Ayah. Menyungkur jatuh, menciumi
dua kaki tua Ayah. Terus menangis sejadi-jadinya.
Adikku
muncul dari dapur dengan wajah keheranan. Kugendong ia mendekati Ibu.
Ayah
bersimpuh, wajahnya lebih dekat pada kami. Kulihat kerutan di dahinya jauh
lebih banyak dari sepuluh tahun lalu. Matanya perlahan memerah, basah. Dan ia
masih Ayahku yang dulu.
ini gambar bukunya lagi. sama sih, biar seru aja!
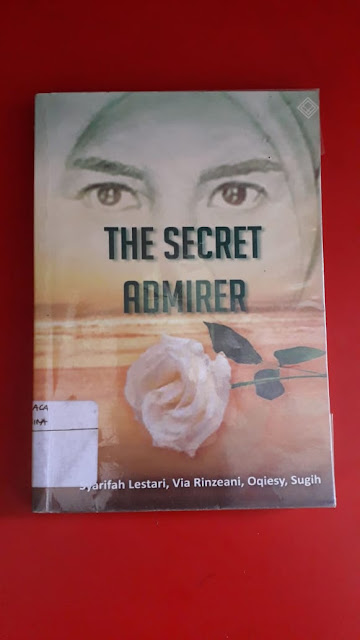 |
| doc by rumbai jambi |








terima kasih masukannya
ReplyDeleteAku aneh baca awalnya. Kayak menceritakan karya orang lain. Hihihi. Karena ku tau namamu makanya ya aku tahu
ReplyDeletegara2 pengantar yg tak berguna itu ya! wkwk
DeletePenulisannya mengalir sekali. Pilihan diksinya juga beragam dan menarik. Cuma saya agak pusing sedikit dengan alurnya.
ReplyDeleteTerima kasih atas bacaannya
bawa tidur aja biar gak pusing
DeleteAwallnya bikin bingung, lalu mengalir dan aku nyaman baca ceritanya kak 😊
ReplyDeleteKeren endingnya.
ReplyDelete